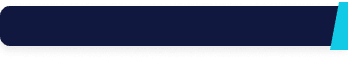Alun-alun Malang, Simbol Perebutan Kekuasaan Belanda dan Jepang

Alun-alun Malang, Simbol Perebutan Kekuasaan Belanda dan Jepang
A
A
A
PEMBENTUKAN kota dipengaruhi konsep-konsep urbanisme, chiefdom, dan asal usul kota. Paul Wheatley menuturkan, konsep urbanisme merupakan integrasi kebudayaan masyarakat yang saling berpengaruh dengan struktur kota yang kemudian menjadi suatu simbol dari kebudayaan masyarakat kota itu sendiri. Urbanisasi dipengaruhi dua hal penting yaitu melalui urbanisasi (urbanization) dan proses urban (urban process).
Wheatley membedakan pembentukan kota yang lebih khusus menjadi dua yaitu sistem paksaan (urban imposition) dan sistem kebangkitan (urban generation). Dalam prosesnya, oleh penguasa urban imposition digunakan untuk mempertahankan sistem nilai kekuasaan.
Sistem paksaan atau commandery yang datang dari luar datang menindas sistem yang sudah ada sebelumnya. Ada ketidakberdayaan nilai-nilai lokal terhadap nonlokal. Penguasa memaksakan suatu nilai yang memudahkan pengawasan demi pengendalian dan mempertahankan kekuasaannya.
Sementara urban generation merupakan bentuk perubahan yang sistematik (bukan dari paksaan) dan tumbuh dari dalam kelompok warga kota. Dalam konsep Wheatley, ini disebut sebagai sistem kebangkitan (nagara). Dalam sistem ini, seluruh penataan sesuai dengan kebudayaan dan ruang kota dibagi sesuai dengan lapisan sosial serta tata nilai yang dipahami warga.
Pergulatan urban imposition dan urban generation ini bisa dilihat di Kota Malang saat penjajahan Belanda serta Jepang.
Awalnya Malang merupakan sebuah daerah berbentuk kerajaan yang dipimpin Raja Gajayana dengan pusat pemerintahan di Dinoyo. Lalu pada 1767, Belanda datang dan pada 1821 pemerintahan Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas. Dua tahun setelah itu, Malang telah mempunyai asisten residen.
Selanjutnya sekitar 1882, Alun-Alun Kota Malang dibangun dan rumah-rumah di bagian barat kota pun didirikan. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah ”Gemente” (Kota).
Malang sebagai kota pedalaman (inland city) yang dikembangkan menjadi kota hunian dan peristirahatan mempunyai derajat pertumbuhan yang lebih lambat namun terencana karena lokasi geografisnya nyaman dan teduh. Namun keluarnya Undang-Undang Gula tahun 1870 yang mendorong pengembangan masuknya modal swastas asing ke Hindia, menjadikan Malang kota pusat perkebunan yang cocok untuk kopi, kakao, dan teh.
Berdasarkan teori Wheatley, perkembangan kota diawali dari penekanan pada pertumbuhan dan struktur jejaring tertentu (interaksi), kemudian gaya hidup berkembang (normatif), muncul lokasi produksi dan pusat kegiatan jasa (ekonomi), berlanjut pada penambahan populasi penduduknya (demografi). Malang pun mulai berkembang pesat saat kereta api sudah beroperasi sekitar 1879. Jalur kereta api mempermudah interaksi Malang dengan kota-kota lainnya.
Hal ini berlanjut dengan adanya migrasi penduduk karena faktor ekonomi. Jumlah penduduk pun meningkat pesat. Sejak saat itulah berbagai kebutuhan warga kota Malang semakin meningkat.
Sejalan dengan itu, terjadilah arus urbanisasi yang semakin tinggi di kota ini. Terjadi pula perubahan fungsi lahan pertanian kemudian berubah menjadi perumahan dan industri.
Perubahan Konsepsi Alun-alun dari Nagara ke Commandery
Pada konsepsi kutha-negara di Indonesia selalu memiliki apa yang disebut alun-alun. Kosakata alun-alun ini berasal dari kata halun-halun.
Secara harfiah kata halun-halun pada zaman kutha-negara yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang menurut Wiryomartono dalam bukunya ”Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia” memiliki sifat telaga dengan riak yang tenang. Sifat tersebut merupakan sebuah cerminan sebagai integrator segara keragaman: peran, aspirasi, dan tradisi.
Urban generation pada konsepsi alun-alun tersebut terlebih muncul saat Hindu-Budha masuk ke Indonesia. Banyak ritual keagamaan, penobatan raja dan ratu, perkawinan adat, dan penyambutan tamu-tamu agung dilakukan di tempat tersebut.
Selain itu alun-alun, menurut konsep Jawa, merupakan simbol kekuasaan karena letaknya persis di depan siti hinggil keraton atau depan pendopo kabupaten. Apabila keraton atau pendopo diibaratkan rumah, maka alun-alun merupakan halamannya.
Purnawan Basundoro mengutip penelitian Jo Santoso menyimpulkan, menurut konsep Jawa, pertama alun-alun melambangkan ditegakkannya sebuah sistem kekuasaan atas sebuah wilayah kekuasaan terhenti, sekaligus menggambarkan tujuan penegakan atas sistem kekuasaan berupa harmonisasi mikrokosmos dan makrokosmos.
Kedua, alun-alun berfungsi sebagai tempat semua perayaan ritual atau upacara keagamaan yang penting. Ketiga, alun-alun merupakan tempat mempertontonkan kekuasaan militer yang bersifat profan dan merupakan instrumen kekuasaan dalam mempraktikkan kekuasaan sakral penguasa.
![Alun-alun Malang, Simbol Perebutan Kekuasaan Belanda dan Jepang]()
Mengutip Soemarsiad Moertono dalam Mataram Islam, Purnawan Basundoro mengemukakan alun-alun merupakan salah satu sarana material yang digunakan untuk kultus kemegahan raja. Di alun-alun, tamu-tamu raja yang akan menghadap menunggu sehingga alun-alun disebut juga paseban (tempat menunggu). Bagi rakyat kecil, kawulo kerajaan, alun-alun dianggap juga sebagai simbol ruang untuk mengadu nasib karena di sini melakukan protes atas ketidakadilan yang dia terima.
Sebagai salah satu simbol kekuasaan, maka konsepsi alun-alun pun tidak luput menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda. Mereka memanfaatkan alun-alun sebagai penggambaran atas munculnya kekuasaan baru di Jawa.
Rumah residen atau asisten residen dibangun berhadapan langsung dengan ketaron atau pendopo kabupaten. Akibatnya, kekuasaan penguasa tradisional Jawa yang mulai runtuh semakin pudar dengan hadirnya simbol kekuasaan baru di sekitar alun-alun.
Salah satu desain yang juga sangat berbau Belanda dan menabrak pakem Jawa adalah alun-alun Kota Malang. Letak bangunan penting, seperti pendopo kabupaten berada di sebelah timur dan tidak menghadap alun-alun. Sementara letak kantor asisten residen di sebelan selatan alun-alun.
Tentu saja hal ini menyalahi prinsip-prinsip tata ruang Jawa, yang selalu menempatkan alun-alun di utara keraton atau pendopo kabupaten. Ini terkait dengan kota-kota di Jawa yang dibangun menghadap ke utara dan membelakangi laut selatan.
Maka jelas alun-alun Malang dibangun untuk menunjukkan semakin berkuasanya Pemerintah Kolonial Belanda. Lebih jelas mengenai tata letak bangunan di sekitar alun-alun, kantor residen berada di sebelah selatan dan berorientasi langsung ke alun-alun.
Sebelah barat masjid bersebelahan dengan rumah-rumah pengurus masjid. Bagian timur laut terdapat penjara dan utara dibangun gereja. Sementara pendopo kabupaten agak jauh di sebelah timur alun-alun dan menghadap selatan.
Dengan desain sedemikian rupa, sebagai sebuah pusat kota maka alun-alun Malang sejak awal dipakai untuk membentuk citra kekuasaan kolonial. Alun-alun sebagai pusat kota sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
Tak berapa lama, kawasan sekitar alun-alun menjadi kegiatan yang berbau kolonial dengan dibangunnya Societeit Concordia dan Bioscoop Rex. Dansa, biliar, permainan kartu, dan berbagai pertemuan warga kolonial digelar di seputar alun-alun.
Kondisi ini memunculkan kesadaran warga pribumi bahwa mereka berada dalam kekuasaan kolonial Belanda. Kesadaran ini makin membesar manakala ada larangan bagi penduduk pribumi masuk ke kawasan kolonial.
Kultur kolonial yang dibangun di seputar alun-alun itu memunculkan perlawanan dari warga pribumi. Seperti halnya kaum kolonial yang biasa mencari hiburan dan melepas penat di societet, para pribumi menjadikan alun-alun sebagai ruang interaksi mereka. Mereka minum kopi atau makanan lainnya yang dijajakan para pedagang. Jika penjajah Belanda menonton film tanpa suara, para pribumi juga menikmati cita rasa seni lewat ludruk di pojok alun-alun.
Citra kolonial yang ingin dibangun melalui alun-alun luntur bersamaan dengan ”pendudukan” alun-alun oleh warga pribumi. Dengan hilangnya citra itu, pemerintah kolonial di kemudian membangun alun-alun bunder (alun-alun tugu). Di lokasi ini, mereka memusatkan seluruh kegiatan kolonial. Yang mengejutkan, konsep alun-alun bunder ini mengikuti pola alun-alun kota-kota di Jawa.
Bukti bahwa alun-alun besar tidak lagi dicitrakan sebagai simbol kekuasaan yakni dikeluarkannya wilayah alun-alun dari rencana pembangunan kota Malang yang dibagi menjadi beberapa zona. Berbagai perayaan besar tidak lagi digelar di alun-alun besar. Hampir tidak ada lagi kegiatan warga kolonial yang dilakukan di sekitar alun-alun setelah kawasan ini sepenuhnya dikuasai pribumi.
Bukti lain alun-alun besar sengaja diabaikan adalah dikeluarkannya kawasan alun-alun besar dari rencana pembangunan Kota malang yang terbagi dalam beberapa zona. Dalam pembagian zona itu, kawasan alun-alun berada di luar dan tidak masuk dalam rencana pembangunan.
Saat Jepang masuk ke Malang, mereka juga menyadari bahwa alun-alun besar merupakan alun-alun rakyat. Kondisi ini dimanfaatkan Jepang dengan menjadikan alun-alun besar sebagai tujuan utama mereka saat memasuki Malang. Bukan alun-alun bunder yang menjadi pusat pemerintahan Belanda.
Bagi Jepang, kawasan alun-alun bunder harus dibersihkan sekaligus dijauhi untuk memutus rantai kolonialisme Belanda. Strategi brilian untuk merangkul ”saudara mudanya” itu.
Dengan lebih mengakui alun-alun besar dibandingkan alun-alun bunder, pribumi Malang menganggap ”saudara tuanya” itu telah membebaskan mereka dari penjajahan. Alun-alun terbukti menjadi media untuk memperlihatkan kemesraan warga pribumi dengan Jepang meski hanya sesaat.
Karena situasi berikutnya adalah kelanjutan penderitaan penduduk pribumi. Di alun-alun besar inilah, tentara Jepang menunjukkan kekejamannya terhadap ”saudara mudanya”. Kekejaman yang bahkan lebih sadis dari kolonial Belanda. Di zaman Jepang, alun-alun telah merosot nilainya. Bukan hanya bagi penjajah Jepang, tapi juga penduduk pribumi.
Memasuki masa kemerdekaan, alun-alun menjadi area untuk mengekspresikan kebebasan. Tindakan selanjutnya yakni menaklukkan gedung-gedung yang berbau kolonial. Bioscoop Rex diubah namanya menjadi Bioskop Ria. Societeit Condordia menjadi Gedung Rakyat.
Alun-alun Malang menjadi salah satu contoh bagaimana para penguasa menunjukkan kekuasaan mereka. Karena berada di pusat kekuasaan, alun-alun diposisikan sesuai keinginan penguasa. Entah secara halus, seperti dalam konsepsi Jawa maupun brutal selama masa penjajahan Jepang.
Tak mengherankan jika alun-alun menjadi arena pamer kekuasaan, baik secara simbolik maupun nyata, seperti yang dilakukan penjajah Jepang yang sering menghukum penduduk pribumi di alun-alun. Dari sini konsep alun-alun dalam nagara berakhir dan berganti menjadi commandery.
Daftar pustaka:
- Wheatley, Paul. 1983. Nagara and Commandery: Origins of the Southeast Asian Urban Traditions. Chicago. The University of Chicago, Department of Geography.
- Habermas, Jürgen. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Polity. Cambridge.
- Basundoro, Purnawan. 2009. Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan. Yogyakarta. Ombak
- Halomalang.com
Wheatley membedakan pembentukan kota yang lebih khusus menjadi dua yaitu sistem paksaan (urban imposition) dan sistem kebangkitan (urban generation). Dalam prosesnya, oleh penguasa urban imposition digunakan untuk mempertahankan sistem nilai kekuasaan.
Sistem paksaan atau commandery yang datang dari luar datang menindas sistem yang sudah ada sebelumnya. Ada ketidakberdayaan nilai-nilai lokal terhadap nonlokal. Penguasa memaksakan suatu nilai yang memudahkan pengawasan demi pengendalian dan mempertahankan kekuasaannya.
Sementara urban generation merupakan bentuk perubahan yang sistematik (bukan dari paksaan) dan tumbuh dari dalam kelompok warga kota. Dalam konsep Wheatley, ini disebut sebagai sistem kebangkitan (nagara). Dalam sistem ini, seluruh penataan sesuai dengan kebudayaan dan ruang kota dibagi sesuai dengan lapisan sosial serta tata nilai yang dipahami warga.
Pergulatan urban imposition dan urban generation ini bisa dilihat di Kota Malang saat penjajahan Belanda serta Jepang.
Awalnya Malang merupakan sebuah daerah berbentuk kerajaan yang dipimpin Raja Gajayana dengan pusat pemerintahan di Dinoyo. Lalu pada 1767, Belanda datang dan pada 1821 pemerintahan Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas. Dua tahun setelah itu, Malang telah mempunyai asisten residen.
Selanjutnya sekitar 1882, Alun-Alun Kota Malang dibangun dan rumah-rumah di bagian barat kota pun didirikan. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah ”Gemente” (Kota).
Malang sebagai kota pedalaman (inland city) yang dikembangkan menjadi kota hunian dan peristirahatan mempunyai derajat pertumbuhan yang lebih lambat namun terencana karena lokasi geografisnya nyaman dan teduh. Namun keluarnya Undang-Undang Gula tahun 1870 yang mendorong pengembangan masuknya modal swastas asing ke Hindia, menjadikan Malang kota pusat perkebunan yang cocok untuk kopi, kakao, dan teh.
Berdasarkan teori Wheatley, perkembangan kota diawali dari penekanan pada pertumbuhan dan struktur jejaring tertentu (interaksi), kemudian gaya hidup berkembang (normatif), muncul lokasi produksi dan pusat kegiatan jasa (ekonomi), berlanjut pada penambahan populasi penduduknya (demografi). Malang pun mulai berkembang pesat saat kereta api sudah beroperasi sekitar 1879. Jalur kereta api mempermudah interaksi Malang dengan kota-kota lainnya.
Hal ini berlanjut dengan adanya migrasi penduduk karena faktor ekonomi. Jumlah penduduk pun meningkat pesat. Sejak saat itulah berbagai kebutuhan warga kota Malang semakin meningkat.
Sejalan dengan itu, terjadilah arus urbanisasi yang semakin tinggi di kota ini. Terjadi pula perubahan fungsi lahan pertanian kemudian berubah menjadi perumahan dan industri.
Perubahan Konsepsi Alun-alun dari Nagara ke Commandery
Pada konsepsi kutha-negara di Indonesia selalu memiliki apa yang disebut alun-alun. Kosakata alun-alun ini berasal dari kata halun-halun.
Secara harfiah kata halun-halun pada zaman kutha-negara yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang menurut Wiryomartono dalam bukunya ”Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia” memiliki sifat telaga dengan riak yang tenang. Sifat tersebut merupakan sebuah cerminan sebagai integrator segara keragaman: peran, aspirasi, dan tradisi.
Urban generation pada konsepsi alun-alun tersebut terlebih muncul saat Hindu-Budha masuk ke Indonesia. Banyak ritual keagamaan, penobatan raja dan ratu, perkawinan adat, dan penyambutan tamu-tamu agung dilakukan di tempat tersebut.
Selain itu alun-alun, menurut konsep Jawa, merupakan simbol kekuasaan karena letaknya persis di depan siti hinggil keraton atau depan pendopo kabupaten. Apabila keraton atau pendopo diibaratkan rumah, maka alun-alun merupakan halamannya.
Purnawan Basundoro mengutip penelitian Jo Santoso menyimpulkan, menurut konsep Jawa, pertama alun-alun melambangkan ditegakkannya sebuah sistem kekuasaan atas sebuah wilayah kekuasaan terhenti, sekaligus menggambarkan tujuan penegakan atas sistem kekuasaan berupa harmonisasi mikrokosmos dan makrokosmos.
Kedua, alun-alun berfungsi sebagai tempat semua perayaan ritual atau upacara keagamaan yang penting. Ketiga, alun-alun merupakan tempat mempertontonkan kekuasaan militer yang bersifat profan dan merupakan instrumen kekuasaan dalam mempraktikkan kekuasaan sakral penguasa.

Mengutip Soemarsiad Moertono dalam Mataram Islam, Purnawan Basundoro mengemukakan alun-alun merupakan salah satu sarana material yang digunakan untuk kultus kemegahan raja. Di alun-alun, tamu-tamu raja yang akan menghadap menunggu sehingga alun-alun disebut juga paseban (tempat menunggu). Bagi rakyat kecil, kawulo kerajaan, alun-alun dianggap juga sebagai simbol ruang untuk mengadu nasib karena di sini melakukan protes atas ketidakadilan yang dia terima.
Sebagai salah satu simbol kekuasaan, maka konsepsi alun-alun pun tidak luput menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda. Mereka memanfaatkan alun-alun sebagai penggambaran atas munculnya kekuasaan baru di Jawa.
Rumah residen atau asisten residen dibangun berhadapan langsung dengan ketaron atau pendopo kabupaten. Akibatnya, kekuasaan penguasa tradisional Jawa yang mulai runtuh semakin pudar dengan hadirnya simbol kekuasaan baru di sekitar alun-alun.
Salah satu desain yang juga sangat berbau Belanda dan menabrak pakem Jawa adalah alun-alun Kota Malang. Letak bangunan penting, seperti pendopo kabupaten berada di sebelah timur dan tidak menghadap alun-alun. Sementara letak kantor asisten residen di sebelan selatan alun-alun.
Tentu saja hal ini menyalahi prinsip-prinsip tata ruang Jawa, yang selalu menempatkan alun-alun di utara keraton atau pendopo kabupaten. Ini terkait dengan kota-kota di Jawa yang dibangun menghadap ke utara dan membelakangi laut selatan.
Maka jelas alun-alun Malang dibangun untuk menunjukkan semakin berkuasanya Pemerintah Kolonial Belanda. Lebih jelas mengenai tata letak bangunan di sekitar alun-alun, kantor residen berada di sebelah selatan dan berorientasi langsung ke alun-alun.
Sebelah barat masjid bersebelahan dengan rumah-rumah pengurus masjid. Bagian timur laut terdapat penjara dan utara dibangun gereja. Sementara pendopo kabupaten agak jauh di sebelah timur alun-alun dan menghadap selatan.
Dengan desain sedemikian rupa, sebagai sebuah pusat kota maka alun-alun Malang sejak awal dipakai untuk membentuk citra kekuasaan kolonial. Alun-alun sebagai pusat kota sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
Tak berapa lama, kawasan sekitar alun-alun menjadi kegiatan yang berbau kolonial dengan dibangunnya Societeit Concordia dan Bioscoop Rex. Dansa, biliar, permainan kartu, dan berbagai pertemuan warga kolonial digelar di seputar alun-alun.
Kondisi ini memunculkan kesadaran warga pribumi bahwa mereka berada dalam kekuasaan kolonial Belanda. Kesadaran ini makin membesar manakala ada larangan bagi penduduk pribumi masuk ke kawasan kolonial.
Kultur kolonial yang dibangun di seputar alun-alun itu memunculkan perlawanan dari warga pribumi. Seperti halnya kaum kolonial yang biasa mencari hiburan dan melepas penat di societet, para pribumi menjadikan alun-alun sebagai ruang interaksi mereka. Mereka minum kopi atau makanan lainnya yang dijajakan para pedagang. Jika penjajah Belanda menonton film tanpa suara, para pribumi juga menikmati cita rasa seni lewat ludruk di pojok alun-alun.
Citra kolonial yang ingin dibangun melalui alun-alun luntur bersamaan dengan ”pendudukan” alun-alun oleh warga pribumi. Dengan hilangnya citra itu, pemerintah kolonial di kemudian membangun alun-alun bunder (alun-alun tugu). Di lokasi ini, mereka memusatkan seluruh kegiatan kolonial. Yang mengejutkan, konsep alun-alun bunder ini mengikuti pola alun-alun kota-kota di Jawa.
Bukti bahwa alun-alun besar tidak lagi dicitrakan sebagai simbol kekuasaan yakni dikeluarkannya wilayah alun-alun dari rencana pembangunan kota Malang yang dibagi menjadi beberapa zona. Berbagai perayaan besar tidak lagi digelar di alun-alun besar. Hampir tidak ada lagi kegiatan warga kolonial yang dilakukan di sekitar alun-alun setelah kawasan ini sepenuhnya dikuasai pribumi.
Bukti lain alun-alun besar sengaja diabaikan adalah dikeluarkannya kawasan alun-alun besar dari rencana pembangunan Kota malang yang terbagi dalam beberapa zona. Dalam pembagian zona itu, kawasan alun-alun berada di luar dan tidak masuk dalam rencana pembangunan.
Saat Jepang masuk ke Malang, mereka juga menyadari bahwa alun-alun besar merupakan alun-alun rakyat. Kondisi ini dimanfaatkan Jepang dengan menjadikan alun-alun besar sebagai tujuan utama mereka saat memasuki Malang. Bukan alun-alun bunder yang menjadi pusat pemerintahan Belanda.
Bagi Jepang, kawasan alun-alun bunder harus dibersihkan sekaligus dijauhi untuk memutus rantai kolonialisme Belanda. Strategi brilian untuk merangkul ”saudara mudanya” itu.
Dengan lebih mengakui alun-alun besar dibandingkan alun-alun bunder, pribumi Malang menganggap ”saudara tuanya” itu telah membebaskan mereka dari penjajahan. Alun-alun terbukti menjadi media untuk memperlihatkan kemesraan warga pribumi dengan Jepang meski hanya sesaat.
Karena situasi berikutnya adalah kelanjutan penderitaan penduduk pribumi. Di alun-alun besar inilah, tentara Jepang menunjukkan kekejamannya terhadap ”saudara mudanya”. Kekejaman yang bahkan lebih sadis dari kolonial Belanda. Di zaman Jepang, alun-alun telah merosot nilainya. Bukan hanya bagi penjajah Jepang, tapi juga penduduk pribumi.
Memasuki masa kemerdekaan, alun-alun menjadi area untuk mengekspresikan kebebasan. Tindakan selanjutnya yakni menaklukkan gedung-gedung yang berbau kolonial. Bioscoop Rex diubah namanya menjadi Bioskop Ria. Societeit Condordia menjadi Gedung Rakyat.
Alun-alun Malang menjadi salah satu contoh bagaimana para penguasa menunjukkan kekuasaan mereka. Karena berada di pusat kekuasaan, alun-alun diposisikan sesuai keinginan penguasa. Entah secara halus, seperti dalam konsepsi Jawa maupun brutal selama masa penjajahan Jepang.
Tak mengherankan jika alun-alun menjadi arena pamer kekuasaan, baik secara simbolik maupun nyata, seperti yang dilakukan penjajah Jepang yang sering menghukum penduduk pribumi di alun-alun. Dari sini konsep alun-alun dalam nagara berakhir dan berganti menjadi commandery.
Daftar pustaka:
- Wheatley, Paul. 1983. Nagara and Commandery: Origins of the Southeast Asian Urban Traditions. Chicago. The University of Chicago, Department of Geography.
- Habermas, Jürgen. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Polity. Cambridge.
- Basundoro, Purnawan. 2009. Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan. Yogyakarta. Ombak
- Halomalang.com
(poe)