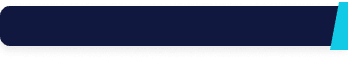Kisah Sepeda Tua dan Perjumpaan Soekarno dengan Marhaenisme

Kisah Sepeda Tua dan Perjumpaan Soekarno dengan Marhaenisme
A
A
A
SEPEDA merupakan bagian kecil dari kehidupan Presiden Soekarno yang sangat penting. Saat sedang asyik bersepeda, Soekarno kerap mengalami berbagai peristiwa tidak terlupakan. Di antaranya saat bertemu dengan pemuda Marhaen.
Dalam buku Kuantar ke Gerbang, Inggit Ganarsih menceritakan, dengan wajah penuh gembira Bung Karno bercerita bahwa dirinya habis mengayuh sepeda ke Cigereleng sampai di Desa Cibintinu dan bertemu dengan petani yang masih muda bernama Marhaen.
Dengan penuh semangat, Soekarno menceritakan kesannya setelah bertemu pemuda Marhaen. Dia menggambarkan sosok Marhaen sebagai petani kecil dengan milik kecil, dan punya alat-alat kecil sekadar cukup untuk dirinya sendiri.
Penghasilan petani Marhaen juga kecil, sekadar cukup untuk dirinya sendiri dan mengganjal perut keluarganya. Tidak ada yang lebihnya sedikit pun. Dia juga tidak bekerja untuk orang lain dan tidak ada orang lain yang bekerja untuknya.
Singkat kata, pada diri Marhaen tidak ada pengisapan tenaga dari seseorang oleh orang lain. "Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik," tegas Soekarno kepada Inggit, seperti dikutip dalam halaman 57.
Pertemuan antara Soekarno dengan petani Marhaen juga diceritakan dalam buku Untold Story, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Saat itu Soekarno sedang mendayung sepeda, sambil berpikir, tanpa tujuan di selatan Kota Bandung.
Daerah yang dilalui sepeda Soekarno adalah kawasan pertanian yang padat, di mana orang bisa menyaksikan para petani mengerjakan sawahnya yang kecil, yang masing-masing luasnya kurang dari sepertiga hektare.
Saat itu, perhatian Soekarno tertuju pada seorang petani yang sedang mencangkul tanah miliknya. Petani itu bekerja seorang diri, dan pakaiannya sudah lusuh. Setelah menghentikan aju sepedanya, Soekarno sempat memperhatikannya dengan diam.
Kemudian Soekarno mendekati petani itu dan berbicara dengannya menggunakan bahasa Sunda. "Siapa yang punya semua yang engkau kerjakan sekarang ini?" kata Soekarno kepada petani itu. "Saya, juragan," jawab petani itu.
Soekarno melanjutkan, "Apakah engkau memiliki tanah ini bersama-sama dengan orang lain?" Dijawab, "O, tidak, gan. Saya sendiri yang punya." "Tanah ini kau beli?" sambung Soekarno. "Tidak. Warisan bapak kepada anak turun temurun," tegasnya.
Usai percakapan singkat itu, petani Marhaen melanjutkan pekerjaannya mencangkul sawah. Sementara Soekarno diam sejenak, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sedang dipikirkannya saat bersepeda tadi. Percakapan pun dimulai lagi.
"Bagaimana dengan sekopmu? Sekop ini kecil, tapi apa ini kepunyaanmu juga?" tanya Soekarno. "Ya, gan," jawabnya. "Dan cangkul?" sambungnya. "Ya, gan," jawabnya. "Bajak?" tambah Soekarno. "Saya punya, gan," katanya.
"Untuk siapa hasil yang kaukerjakan?" sambung Soekarno lagi. "Untuk saya, gan," jawabnya. "Apakah cukup untuk kebutuhanmu?" tanya Soekarno mendesak. Pernyataan itu sempat membuat petani Marhaen diam dan berpikir sejenak.
"Bagaimana sawah yang begini kecil bisa cukup untuk seorang istri dan empat orang anak?" jawab petani itu segera dengan pertanyaan. Setelah mendengar jawaban itu, Soekarno kembali melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya.
"Apakah ada yang dijual dari hasilmu?" katanya. "Hasilnya sekadar cukup untuk makan kami. Tidak ada lebihnya untuk dijual," jawabnya. "Kau pekerjakan orang lain?" sambungnya. "Tidak, juragan. Saya tidak dapat membayarnya," jawabnya.
"Apakah engkau pernah memburuh?" sambung Soekarno memburu. "Tidak, gan. Saya harus membanting tulang, akan tetapi jerih payah saya semua untuk saya," jawab petani Marhaen lagi. Soekarno diam sebentar dan mengalihkan pandangannya.
Dia melihat ke arah gubuk yang berada tidak jauh dari tempat petani itu membajak sawahnya. "Siapa yang punya rumah itu?" tanya Soekarno lagi. "Itu gubuk saya, gan. Hanya gubuk kecil saja, tapi kepunyaan saya sendiri," jawabnya merasa bangga.
Jauh di dalam hati dan pikirannya, Soekarno merasa bangga dengan petani itu. Dia memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. "Jadi kalau begitu, semua ini engkau punya?" kata Soekarno melanjutkan. "Ya, gan," jawab petani itu.
Dalam percakapan itu, karena terlalu asyik dengan pikirannya sendiri dan sejumlah pertanyaan yang ingin ditahuinya, Soekarno hampir lupa menanyakan siapa nama petani muda itu. Setelah ditanya, petani itu menjawab, "Marhaen."
Selesai dengan percakapan itu, Soekarno pamit pulang. Selama dalam perjalanan pulang itu, dia membatin di atas sadel sepedanya. "Aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang seperti dia!" katanya.
Sepanjang hari, setelah pertemuan itu, Soekarno masih suka mengayuh sepeda tuanya berkeliling kampung. Di atas sadelnya, dia terus berpikir untuk membangun konsep marhaenisme dan memaparkannya dalam suatu rapat pemuda.
"Para petani kita mengusahakan bidang tanah yang sangat kecil sekali. Mereka adalah korban dari sistem feodal, di mana pada awalnya petani pertama diperas oleh bangsawan yang pertama, dan seterusnya sampai ke anak cucunya," terangnya.
Rakyat yang bukan petani pun menjadi korban dari imperialisme Belanda, karena nenek moyangnya dipaksa untuk hanya bergerak di bidang usaha kecil. Rakyat yang menjadi korban ini, yang meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia, adalah Marhaen.
"Seorang Marhaen adalah orang yang memiliki alat-alat yang sedikit, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekadar cukup untuk dirinya sendiri," kata Soekarno setelah berhasil merumuskan gagasannya tentang Marhaen.
Lebih jauh, Soekarno menganggap, konsep marhaenisme yang ditemukannya itu adalah bentuk perwujudan sosialisme Indonesia. "Tidak ada penghisapan tenaga seseorang oleh orang lain. Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik," katanya.
Pertemuan Soekarno dengan pemuda Marhaen dan gagasannya tentang marhaenisme berlangsung saat usianya masih sangat muda, yakni 20 tahun. Pada masa ini, Soekarno telah memasuki tahap baru dalam perkembangan politiknya, mengarah marxisme.
Sebelum 1932, kata marhaenisme tidak pernah terdengar di Indonesia. Namun setelah itu, kata ini kerap mewarnai sejumlah perdebatan. Secara luas, kata itu mulai dipopulerkan Soekarno saat menghadapi sidang Pengadilan Kolonial Belanda.
"Marhaenisme adalah pergaulan hidup yang sebagian besar sekali terdiri dari kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil.. Pendek kata, kaum kromo dan kaum marhaen yang apa-apanya semua kecil," katanya.
Marhaenisme, bagi Soekarno sama dengan proletar dalam bahasa kaum marxisme-leninisme. Kata itu digunakan untuk menyebut golongan rakyat yang tertindas. Namun, bedanya Marhaen tidak menjual tenaganya kepada orang lain, tetapi hidupnya miskin.
Tinjauan kritis tentang marxisme yang di-Indonesiakan oleh Soekarno dalam marhaenisme, dilakukan oleh Profesor Sejarah pada Universitas Passau, Jerman Barat, Bernhard Dahm dalam bukunya Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan.
Menurut Dham, pendekatan Soekarno terhadap marhaenisme, meskipun bergaya marxisme, sebenarnya bukan marxis. Sebaliknya, pendekatan Soekarno anti-marxisme. Soekarno dinilai tidak tahu cara menempatkan landasan materialistis dari marxisme.
Soekarno bahkan tidak pernah menjadi marxis dan seorang materialis. Sejak semula, meski sering berprilaku sebagai marxis, Soekarno sebenarnya berada dalam kubu idealisme. Kekuatan yang menggerakkannya dalam marhaenisme adalah persatuan.
Hal yang membuat marhaenisme seolah-olah marxisme, berasal dari bacaan Soekarno terhadap marxisme. Baginya, marxisme bukan hanya membuktikan kebobrokan kapitalisme dan imperialisme, tetapi juga menjanjikan suatu harapan dan kemenangan.
Dengan demikian, menjadi jelaslah kekeliruan yang terjadi selama ini antara marhaenisme dengan marxisme. Gagasan persatuan yang menjadi inti dari marhaenisme bersumber dari filsafat Jawa yang sudah ada selama berabad-abad lamanya.
Sumber Tulisan:
* Ramadhan KH, Soekarno: Kuantar ke Gerbang, Penerbit Bentang, Cetakan Pertama, Januari 2014.
* Cindy Adams, Untold Story, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jas Merah (Jangan Lupakan Sejarah), 2013.
* Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Yayasan Bung Karno, Edisi Revisi, Cetakan Kedua 2011.
* Bernhard Dahm, Soerkarno dan Perjuangan Kemerdekaan, LP3ES, Cetakan Pertama, Desember 1987.
Dalam buku Kuantar ke Gerbang, Inggit Ganarsih menceritakan, dengan wajah penuh gembira Bung Karno bercerita bahwa dirinya habis mengayuh sepeda ke Cigereleng sampai di Desa Cibintinu dan bertemu dengan petani yang masih muda bernama Marhaen.
Dengan penuh semangat, Soekarno menceritakan kesannya setelah bertemu pemuda Marhaen. Dia menggambarkan sosok Marhaen sebagai petani kecil dengan milik kecil, dan punya alat-alat kecil sekadar cukup untuk dirinya sendiri.
Penghasilan petani Marhaen juga kecil, sekadar cukup untuk dirinya sendiri dan mengganjal perut keluarganya. Tidak ada yang lebihnya sedikit pun. Dia juga tidak bekerja untuk orang lain dan tidak ada orang lain yang bekerja untuknya.
Singkat kata, pada diri Marhaen tidak ada pengisapan tenaga dari seseorang oleh orang lain. "Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik," tegas Soekarno kepada Inggit, seperti dikutip dalam halaman 57.
Pertemuan antara Soekarno dengan petani Marhaen juga diceritakan dalam buku Untold Story, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Saat itu Soekarno sedang mendayung sepeda, sambil berpikir, tanpa tujuan di selatan Kota Bandung.
Daerah yang dilalui sepeda Soekarno adalah kawasan pertanian yang padat, di mana orang bisa menyaksikan para petani mengerjakan sawahnya yang kecil, yang masing-masing luasnya kurang dari sepertiga hektare.
Saat itu, perhatian Soekarno tertuju pada seorang petani yang sedang mencangkul tanah miliknya. Petani itu bekerja seorang diri, dan pakaiannya sudah lusuh. Setelah menghentikan aju sepedanya, Soekarno sempat memperhatikannya dengan diam.
Kemudian Soekarno mendekati petani itu dan berbicara dengannya menggunakan bahasa Sunda. "Siapa yang punya semua yang engkau kerjakan sekarang ini?" kata Soekarno kepada petani itu. "Saya, juragan," jawab petani itu.
Soekarno melanjutkan, "Apakah engkau memiliki tanah ini bersama-sama dengan orang lain?" Dijawab, "O, tidak, gan. Saya sendiri yang punya." "Tanah ini kau beli?" sambung Soekarno. "Tidak. Warisan bapak kepada anak turun temurun," tegasnya.
Usai percakapan singkat itu, petani Marhaen melanjutkan pekerjaannya mencangkul sawah. Sementara Soekarno diam sejenak, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sedang dipikirkannya saat bersepeda tadi. Percakapan pun dimulai lagi.
"Bagaimana dengan sekopmu? Sekop ini kecil, tapi apa ini kepunyaanmu juga?" tanya Soekarno. "Ya, gan," jawabnya. "Dan cangkul?" sambungnya. "Ya, gan," jawabnya. "Bajak?" tambah Soekarno. "Saya punya, gan," katanya.
"Untuk siapa hasil yang kaukerjakan?" sambung Soekarno lagi. "Untuk saya, gan," jawabnya. "Apakah cukup untuk kebutuhanmu?" tanya Soekarno mendesak. Pernyataan itu sempat membuat petani Marhaen diam dan berpikir sejenak.
"Bagaimana sawah yang begini kecil bisa cukup untuk seorang istri dan empat orang anak?" jawab petani itu segera dengan pertanyaan. Setelah mendengar jawaban itu, Soekarno kembali melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya.
"Apakah ada yang dijual dari hasilmu?" katanya. "Hasilnya sekadar cukup untuk makan kami. Tidak ada lebihnya untuk dijual," jawabnya. "Kau pekerjakan orang lain?" sambungnya. "Tidak, juragan. Saya tidak dapat membayarnya," jawabnya.
"Apakah engkau pernah memburuh?" sambung Soekarno memburu. "Tidak, gan. Saya harus membanting tulang, akan tetapi jerih payah saya semua untuk saya," jawab petani Marhaen lagi. Soekarno diam sebentar dan mengalihkan pandangannya.
Dia melihat ke arah gubuk yang berada tidak jauh dari tempat petani itu membajak sawahnya. "Siapa yang punya rumah itu?" tanya Soekarno lagi. "Itu gubuk saya, gan. Hanya gubuk kecil saja, tapi kepunyaan saya sendiri," jawabnya merasa bangga.
Jauh di dalam hati dan pikirannya, Soekarno merasa bangga dengan petani itu. Dia memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. "Jadi kalau begitu, semua ini engkau punya?" kata Soekarno melanjutkan. "Ya, gan," jawab petani itu.
Dalam percakapan itu, karena terlalu asyik dengan pikirannya sendiri dan sejumlah pertanyaan yang ingin ditahuinya, Soekarno hampir lupa menanyakan siapa nama petani muda itu. Setelah ditanya, petani itu menjawab, "Marhaen."
Selesai dengan percakapan itu, Soekarno pamit pulang. Selama dalam perjalanan pulang itu, dia membatin di atas sadel sepedanya. "Aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang seperti dia!" katanya.
Sepanjang hari, setelah pertemuan itu, Soekarno masih suka mengayuh sepeda tuanya berkeliling kampung. Di atas sadelnya, dia terus berpikir untuk membangun konsep marhaenisme dan memaparkannya dalam suatu rapat pemuda.
"Para petani kita mengusahakan bidang tanah yang sangat kecil sekali. Mereka adalah korban dari sistem feodal, di mana pada awalnya petani pertama diperas oleh bangsawan yang pertama, dan seterusnya sampai ke anak cucunya," terangnya.
Rakyat yang bukan petani pun menjadi korban dari imperialisme Belanda, karena nenek moyangnya dipaksa untuk hanya bergerak di bidang usaha kecil. Rakyat yang menjadi korban ini, yang meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia, adalah Marhaen.
"Seorang Marhaen adalah orang yang memiliki alat-alat yang sedikit, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekadar cukup untuk dirinya sendiri," kata Soekarno setelah berhasil merumuskan gagasannya tentang Marhaen.
Lebih jauh, Soekarno menganggap, konsep marhaenisme yang ditemukannya itu adalah bentuk perwujudan sosialisme Indonesia. "Tidak ada penghisapan tenaga seseorang oleh orang lain. Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik," katanya.
Pertemuan Soekarno dengan pemuda Marhaen dan gagasannya tentang marhaenisme berlangsung saat usianya masih sangat muda, yakni 20 tahun. Pada masa ini, Soekarno telah memasuki tahap baru dalam perkembangan politiknya, mengarah marxisme.
Sebelum 1932, kata marhaenisme tidak pernah terdengar di Indonesia. Namun setelah itu, kata ini kerap mewarnai sejumlah perdebatan. Secara luas, kata itu mulai dipopulerkan Soekarno saat menghadapi sidang Pengadilan Kolonial Belanda.
"Marhaenisme adalah pergaulan hidup yang sebagian besar sekali terdiri dari kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil.. Pendek kata, kaum kromo dan kaum marhaen yang apa-apanya semua kecil," katanya.
Marhaenisme, bagi Soekarno sama dengan proletar dalam bahasa kaum marxisme-leninisme. Kata itu digunakan untuk menyebut golongan rakyat yang tertindas. Namun, bedanya Marhaen tidak menjual tenaganya kepada orang lain, tetapi hidupnya miskin.
Tinjauan kritis tentang marxisme yang di-Indonesiakan oleh Soekarno dalam marhaenisme, dilakukan oleh Profesor Sejarah pada Universitas Passau, Jerman Barat, Bernhard Dahm dalam bukunya Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan.
Menurut Dham, pendekatan Soekarno terhadap marhaenisme, meskipun bergaya marxisme, sebenarnya bukan marxis. Sebaliknya, pendekatan Soekarno anti-marxisme. Soekarno dinilai tidak tahu cara menempatkan landasan materialistis dari marxisme.
Soekarno bahkan tidak pernah menjadi marxis dan seorang materialis. Sejak semula, meski sering berprilaku sebagai marxis, Soekarno sebenarnya berada dalam kubu idealisme. Kekuatan yang menggerakkannya dalam marhaenisme adalah persatuan.
Hal yang membuat marhaenisme seolah-olah marxisme, berasal dari bacaan Soekarno terhadap marxisme. Baginya, marxisme bukan hanya membuktikan kebobrokan kapitalisme dan imperialisme, tetapi juga menjanjikan suatu harapan dan kemenangan.
Dengan demikian, menjadi jelaslah kekeliruan yang terjadi selama ini antara marhaenisme dengan marxisme. Gagasan persatuan yang menjadi inti dari marhaenisme bersumber dari filsafat Jawa yang sudah ada selama berabad-abad lamanya.
Sumber Tulisan:
* Ramadhan KH, Soekarno: Kuantar ke Gerbang, Penerbit Bentang, Cetakan Pertama, Januari 2014.
* Cindy Adams, Untold Story, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jas Merah (Jangan Lupakan Sejarah), 2013.
* Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Yayasan Bung Karno, Edisi Revisi, Cetakan Kedua 2011.
* Bernhard Dahm, Soerkarno dan Perjuangan Kemerdekaan, LP3ES, Cetakan Pertama, Desember 1987.
(san)